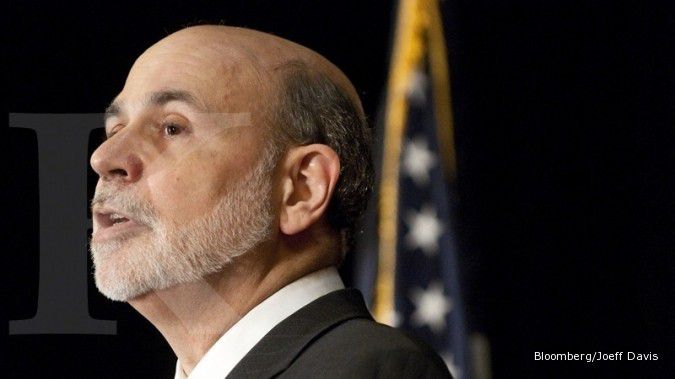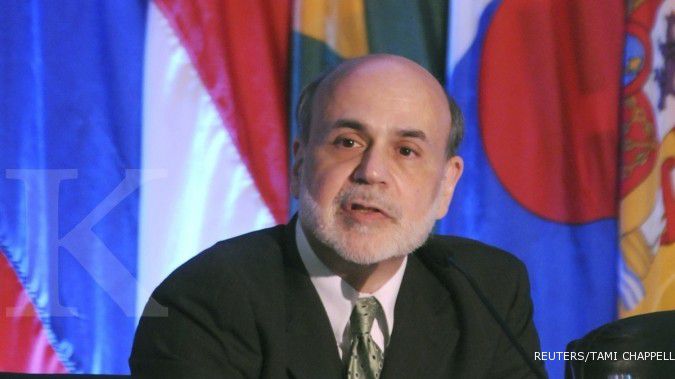JAKARTA. Perekonomian emerging market beberapa waktu belakangan tengah terguncang. Guncangan semakin terasa menjelang pengumuman rapat pimpinan the Federal Reserve yang berlangsung pada 28-29 Januari 2014 lalu. Salah satu buktinya adalah kejatuhan sejumlah mata uang emerging market beberapa waktu lalu seperti Argentina, Turki, Brazil, hingga Afika Selatan. Tidak hanya itu saja, pasar saham emerging juga ikut bergejolak. Kecemasan pun merebak sehingga memicu pertanyaan: apakah hal ini akan menjadi awal krisis finansial global yang baru? Bahkan, sejumlah pakar ekonomi AS menyematkan istilah "flu emerging market" untuk menggambarkan kondisi ini. Pemicu flu: penarikan hot money
Jika ditarik lebih luas lagi, aksi jual besar-besaran tersebut merupakan respon dari aksi pemangkasan nilai stimulus (tapering) the Fed. Sebab, langkah bank sentral AS tersebut menandakan berkurangnya dana panas atau
hot money yang sudah disuntikkan ke dalam sistem finansial global. Pada awal mula penggelontoran stimulus the Fed, banyak investor global yang mencari yield tinggi dengan berinvestasi di emerging market. Namun, pesta telah usai. Aliran dana besar-besaran ke emerging market mulai melambat. Bahkan mungkin bisa berhenti sama sekali. Yilmaz Akyuz,
chief economist South Centre, menganalisa hal ini dalam papernya berjudul: Waving or Drowning? Dalam tulisannya Akyuz menulis, ledakan arus dana asing ke emerging market dimulai pada awal 2000. Namun, sempat terhenti setelah Lehman Brothers bangkrut pada September 2008. Setelah itu, arus dana asing kembali mengalir deras. Pada kurun waktu 2010-2012, nilai arus dana asing yang mengalir ke Asia dan Amerika Latin mencapai puncaknya sebelum terjadi krisis. Hal ini terjadi seiring kebijakan
easy money dan tingkat suku bunga mendekati nol di AS dan Eropa. Di AS, misalnya, the Fed memompa dana senilai US$ 85 miliar per bulan ke sistem perbankan untuk membeli obligasi. Harapannya, perbankan akan menyalurkan dananya ke sejumlah bisnis sehingga dapat memacu pemulihan ekonomi. Nyatanya, investor banyak yang menempatkan dana yang mereka terima di pasar saham dan negara-negara berkembang. Dampaknya, beberapa pasar saham dan mata emerging market mengalami lonjakan yang signifikan. Namun, ada pula emerging market yang kurang beruntung karena dana panas tersebut menyebabkan mata uang mereka menguat sehingga, ekspor mereka menjadi tidak kompetitif. Hingga akhirnya, pada Mei hingga Juni 2013, the Fed mengumumkan akan melakukan pemangkasan
(tapering) nilai stimulus mereka. Kondisi ini menyebabkan kejatuhan nilai mata uang yang tiba-tiba, termasuk di Indonesia. Meski demikian, the Fed menunda pelaksanaan
tapering dengan maksud memberikan waktu yang cukup bagi pelaku pasar untuk bersiap. Hingga akhirnya, tapering benar-benar dilakukan pada Desember dengan nilai pengurangan stimulus sebesar US$ 10 miliar menjadi US$ 75 miliar. Pada waktu itu, pasar sudah mengantisipasi kebijakan the Fed sehingga tidak terjadi
panic selling di pasar saham global dan regional. Selain itu, akan terjadi pula pelemahan mata uang yang akan berdampak positif pada daya saing ekspor. Namun, dampak negatifnya adalah kenaikan tingkat inflasi (seiring lonjakan tingkat ekspor) dan melonjaknya nilai utang (karena banyak perusahaan yang harus membayar utang mereka dalam mata uang asing). "Dalam pandangan kami, masih ada risiko yang belum dapat dihilangkan. Kami memprediksi, kebijakan tapering akan berdampak pada negara-negara yang mengalami defisit besar," jelas Manpreet Gill,
head of fixed income currencies and commodities (FICC) investment strategy Standard Chartered. Sementara itu, Tai Hui,
chief market strategist Asia JPMorgan Funds juga berpendapat sama. "Saya rasa
outflow dana asing tidak akan terlalu buruk. Namun, diferensiasi di antara emerging market akan sangat kritis," jelas Hui. Hui menilai, risiko
outflow dana asing lebih terlihat di pasar obligasi emerging market dibanding pasar saham. Pasalnya, pasar obligasi mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari inflow dana asing seiring diberlakukannya kebijakan pelonggaran moneter dalam empat tahun terakhir. Sedangkan Boris Schlossberg,
manager director BK Asset Management berpendapat berbeda. Dia menilai, tapering yang dilakukan the Fed merefleksikan tingkat kepercayaan the Fed terhadap perekonomian AS. Kondisi ini bisa menjadi hal yang positif bagi mata uang emerging market. "Mata uang emerging market merupakan salah satu pendorong pertumbuhan. Sehingga, jika ekonomi AS bertindak sebagai lokomotif bagi perekonomian global di 2014, maka, hal itu relatif sehat bagi mata uang emerging market," papar Schlossberg. Bagaimana outlook pasar saham emerging? Aksi jual yang melanda emerging market membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah kondisi yang terburuk sudah lewat atau malah sebaliknya. Jika dilihat, Januari merupakan bulan yang buruk bagi pasar saham emerging market. Berdasarkan data yang dirilis EPFR, dana yang hengkang dari pasar saham emerging di bulan pertama tahun ini mencapai US$ 12,2 miliar. Yang perlu diingat, kejatuhan pasar saham juga menyebabkan valuasi saham di emerging semakin menarik. "Memang ada kemungkinan kondisi bisa semakin memburuk. Namun ada catatan, diskon yang terjadi di pasar saham sangat besar. Pasar saham emerging market saat ini sudah terdiskon 40% dibanding pasar saham negara maju," jelas Russ Koesterich, global chief investment strategist BlackRock. Dia menambahkan, diskon tersebut merupakan yang terbesar sejak krisis finansial terjadi. Michael Kurtz,
global head of equity strategy Nomura menambahkan, saham emerging market saat ini memberikan nilai lebih ketimbang saham di negara maju. Dana asing yang keluar dari pasar saham menyebabkan harga saham jatuh ke level rendah. "Kami memprediksi, dengan kondisi tersebut, performa emerging market dapat melampaui performa negara maju dalam 12 bulan ke depan," urainya. Namun, ada kecemasan lain yang harus diperhatikan yakni terkait dengan posisi Produk Domestik Bruto (PDB). "Jika PDB emerging market terus mengalami perlambatan pertumbuhan, maka investor tidak dapat menikmati murahnya harga saham," jelas Kurtz. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia mengejutkan pelaku pasar dengan merilis data PDB yang jauh lebih baik ketimbang prediksi pada Rabu (4/2). Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, pertumbuhan eknomi di kurtal IV-2013 sebesar 5,72%. Sebelumnya Menteri Keuangan Chatib Basri memperkirakan, pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2013 akan sebesar 5,7%. Menurutnya, pelambatan ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk menekan impor. Pencapaian ini mematahkan perkiraan lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF) yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh masing-masing sebesar 5,6% dan 5,3%. Bank DBS optimistis perekonomian Indonesia di tahun ini bisa mencapai target 6%. Laju pertumbuhan konsumsi yang akan terus bertumbuh menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun kuda kayu. Ekonom DBS Gundy Cahyadi mengatakan pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai sebesar 5,78% di 2013 menjadi stimulus yang cukup mendorong prospek pertumbuhan ekonomi 2014. Pertumbuhan konsumsi swasta memang melemah ke 5,25% di triwulan IV 2013 dibanding periode sama tahun lalu. Namun di tahun ini, Gundy melihat laju pertumbuhan konsumsi swasta ini akan meningkat karena adanya pemilihan umum (pemilu) 2014. Sementara itu, data berbeda yang dirilis Bank Indonesia menunjukkan, neraca perdagangan pada Desember 2013 mengalami surplus yang cukup besar. Menurut Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Peter Jacobs, surplus neraca perdagangan naik dari US$ 0,79 miliar pada November menjadi US$ 1,52 miliar pada Desember 2013. Ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono mengungkapkan, kinerja positif ini dikarenakan pelemahan nilai tukar rupiah. "Surplusnya perdagangan Indonesia karena rupiah yang melemah. Bukan karena yang lain, kebijakan fiskal," kata Tony di Jakarta, Senin (3/2). Sesuai data Bank Indonesia, rupiah mengalami pelemahan di atas 20% di sepanjang 2013. Nilai tukar kini bertengger di level Rp 12.260/US$. Depresiasi nilai tukar rupiah ini telah membuat barang-barang non minyak dan gas (migas) dari dalam negeri lebih murah jika dibandingkan luar negeri. Sementara, jika bicara mengenai dampak tapering terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), analis menilai, pelaku pasar sudah siap dengan keputusan the Fed sehingga tidak akan berdampak terlalu besar terhadap IHSG. Pasca pengumuman tapering tahap II pada 29 Januari lalu, IHSG bisa kembali menghijau meski hanya naik 0,03% pada penutupan perdagangan Kamis (30/1) setelah sebelumnya memerah. IHSG ditutup di level 4.418,75 dengan akumulasi net sell investor asing sebesar Rp 154,3 miliar.
David N. Sutyanto, Analis First Asia Capital mengatakan, pasar telah menyesuaikan portofolionya dengan ekspektasi adanya tapering lagi. Namun, tetap saja, dalam jangka pendek, pasar akan merespons kebijakan ini dengan aksi jual di emerging market, termasuk Indonesia. Sehingga, dalam jangka pendek, IHSG diperkirakan akan bergerak volatile dengan kecenderungan koreksi. Untungnya, masih ada beberapa indikator yang bisa mendorong IHSG kembali bullish, yakni adanya sentimen laporan keuangan emiten. "Aksi jual asing akan marak, karena investor sedang ambil posisi, namun tidak lama akan normal lagi," ujar David. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News